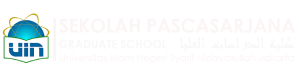Argumen Pembentukan Ditjen Pesantren
Suwendi Dosen UIN Jakarta dan Penulis Buku “Detik-Detik Penetapan Hari Santri”
Kementerian Agama akan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, bernama Ditjen Pesantren. Ditjen ini merupakan elevasi birokrasi dari direktorat atau unit eselon 2 menjadi Ditjen atau unit eselon 1. Pembentukan Ditjen ini perlu diapresiasi bersama, sebab memiliki langkah yang strategis, di samping memang sangat layak didirikan.
Hingga semester genap 2025 ini, Kementerian Agama mencatat pesantren sebanyak 42.369 lembaga, 6.267.741 santri, dan 1.163.140 ustadz. Di samping pesantren, terdapat layanan pendidikan lainnya yang selama ini berada di lingkungan direktorat tersebut, baik pada jalur formal maupun nonformal. Pada jalur formal, terdapat Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Ma’had Aly. Sedangkan layanan pendidikan jalur nonformal terdiri atas Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), Pendidikan Al-Quran, dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).
Hemat penulis, terdapat sejumlah argumen pembentukan Ditjen Pesantren ini. Pertama, peran dan kontribusi pesantren untuk negara dan bangsa, sejak masa perjuangan melawan kaum imperalis, masa kemerdekaan, hingga mengisi kemerdekaan, demikian nyata hingga tidak ada yang dapat membantahnya. Berbagai pertempuran melawan penjajah demi meraih kemerdekaan Indonesia seringkali dimotori oleh para kyai dan santri pesantren. Hingga agresi militer Belanda ke-2 itu dapat dipatahkan oleh perlawanan kyai-santri pesantren, yakni berkat resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Dalam pembangunan pascakemerdekaan pun, pesantren tetap komitmen setia terhadap NKRI dan secara proaktif membangun bangsa. Walhasil, dari rahim pesantrenlah, Indonesia ini didirikan, diasuh, dan dibesarkan hingga saat ini.
Kedua, ketidaksesuaian struktural birokrasi berbanding fungsi yang diemban sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi. UU 18/2019 mengamanatkan bahwa pesantren menjalankan tiga fungsi, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga, oleh karenanya, pendanaan untuk pesantren dapat berasal dari fungsi pendidikan, fungsi agama, dan fungsi lainnya. Posisi Direktorat Pesantren yang selama ini berada di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam hanya menyentuh fungsi pendidikan semata, sehigga oleh karenanya hanya bersumber dari alokasi anggaran fungsi pendidikan. Keterbatasan ini menciptakan kelumpuhan kebijakan yang pada akhirnya pesantren kurang mendapatkan layanan sekaligus peran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
Ketiga, kehadiran negara terhadap pesantren cenderung belum menunjukkan perlakuan yang semestinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan wewenang birokrasi yang selama ini berjalan hingga keterbatasan anggaran. Sungguhpun demikian, dengan segala bentuk independensi dan kemandiriannya, pesantren tetap ikhlas dan istiqamah berdiri tegak untuk membina anak-anak bangsa.
Setidaknya terdapat tiga kesetaraan yang harus dilakukan oleh negara, termasuk terhadap pesantren, yakni rekognisi, afirmasi, dan kebijakan/program. Dalam aspek rekognisi, negara melakukan pengakuan terhadap pendidikan pesantren yang dibuktikan dengan regulasi. Sementara pada aspek afirmasi, dibuktikan dengan kehadiran anggaran dan pembiayaan oleh pemerintah secara berkeadilan. Sedangkan kebijakan/program adalah perlakuan kebijakan dan tatakelola oleh semua stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat, terhadap pesantren.
Kehadiran negara pada aspek rekognisi demikian nyata, yakni dengan lahirnya UU 18/2019 tentang Pesantren, bahkan sebelumnya didahului Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang hari santri. Kedua regulasi ini, yang kemudian diikuti dengan aturan turunannya, menunjukkan keseriusan negara dalam mengakui sistem dan pendidikan pesantren.
Sungguhpun demikian, pada aspek afirmasi dan kebijakan/program terhadap pesantren, hemat penulis terdapat catatan serius yang perlu dipertimbangkan. Afirmasi anggaran belum berdampak, meskipun telah lahir UU 18/2019. Hal ini dibuktikan dengan rasio alokasi anggaran fungsi pendidikan dibanding dengan anggaran untuk pesantren yang tidak signifikan. Di tahun 2024, alokasi fungsi pendidikan sebanyak 660,8 T ternyata untuk layanan pesantren tidak lebih dari 1,021 T atau 0,15% saja. Demikian juga di tahun 2023, yakni dari 612,2 T anggaran fungsi pendidikan itu untuk layanan pesantren hanya 877 M atau 0,14%. Jadi, kehadiran negara secara finansial hanya dikisaran 0,1% saja. Hal ini berbeda jauh dengan layanan pendidikan lainnya, seperti sekolah umum. Di tahun 2022, dari 419,4 T alokasi fungsi pendidikan ternyata digunakan untuk sekolah umum sebesar 365,5 T atau 86,75%. Di tahun 2021, dari 437,9 T alokasi fungsi pendidikan digunakan untuk sekolah umum sebesar 380,6 T atau 86,91%.
Kondisi ini lebih disebabkan oleh regulasi pendanaan yang tidak berpihak, terlebih mengafirmasi, terhadap pendanaan pesantren. Regulasi tersebut di antaranya UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2oo8 Tentang Pendanaan Pendidikan. Hemat penulis, sejauh kedua regulasi ini tidak dilakukan perubahan maka pesantren berpotensi tidak akan banyak mendapatkan pembiayaan yang semestinya dari negara.
Pada aspek kebijakan/program, jenis pendidikan pesantren melalui jalur formal berupa PDF (Pendidikan Diniyah Formal), SPM (Satuan Pendidikan Muadalah), dan MA (Ma’had Aly) sebagaimana diatur dalam UU 18/2019 sesungguhnya telah memiliki kesetaraan terutama civil effect dan anggaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa lulusan jenis pendidikan pesantren tersebut belum sepenuhnya diakui, baik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi maupun untuk dunia kerja. Lulusan PDF dan SPM belum sepenuhnya dapat melanjutkan ke sekolah/madrasah jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi. Lulusan Ma’had Aly belum sepenuhnya dapat melanjutkan S2 atau S3 pada perguruan tinggi, termasuk di bawah naungan Kemendiktisaintek dan dunia kerja formal seperti ASN atau perusahaan. Demikian juga, hak-hak yang melekat untuk semua jenis pendidikan formal diperlakukan yang sama. Sebagaimana sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, PDF, SPM, dan Ma’had Aly berhak mendapatkan BOS, tunjangan sertifikasi guru/dosen, BOPTN dan Bidik Misi. Kendala-kendala ini dapat dimaklumi di antaranya oleh karena keterbatasan anggaran yang sangat minimal tersebut.
Keempat, kehadiran negara yang kurang optimal terhadap pesantren terlebih dalam durasi yang demikian panjang, baik yang disebabkan karena keterbatasan kewenangan birokrasi maupun anggaran sebagaimana disebutkan di atas, secara perlahan dan pasti pada akhirnya akan merugikan pesantren, negara, dan bangsa Indonesia sendiri. Pesantren berpotensi akan kehilangan elan vital dan jati dirinya. Di samping itu, upaya mendestruksi pesantren terutama dari luar pesantren semakin nyata. Jika hal demikian terjadi, maka pesantren sebagai penyanggah utama negara kesatuan RI, baik aspek ideologi, moral, dan pengetahuan akan semakin rapuh.
Atas dasar sejumlah argumen di atas, perombakan birokasi menjadi Ditjen Pesantren menjadi keniscayaan strategis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Langkah ini tidak hanya untuk ruang gerak yang lebih terbuka bagi institusi Kementerian Agama semata, tetapi pada akhirnya pesantren, masyarakat, dan negara akan semakin berdaya dan kokoh. Semoga