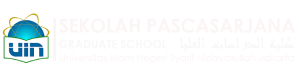Studium Generale Cyberfaith among Muslim Millenials: Gen-Z Indonesia Jadikan Internet sebagai Ruang Ibadah Baru
Auditorium Prof. Dr. Suwito, MA SPs UIN Jakarta, SPs NEWS - Sebuah pergeseran fundamental sedang terjadi dalam lanskap keberagamaan di Indonesia. Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Studium Generale bertajuk "Cyberfaith among Muslim Millennial" pada Rabu, 19 November 2025. Bertempat di Auditorium Prof. Dr. Suwito, MA, acara ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menandai tonggak sejarah baru dengan peresmian Indonesian Lab of Anthropo-psychology of Religion and Spirituality.
Direktur SPs UIN Jakarta, Prof. Dr. Zulkifli, MA, membuka acara dengan penuh antusiasme. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa forum ini adalah wujud nyata komitmen institusi untuk menjembatani psikologi, budaya, dan iman. Laboratorium baru yang digagas oleh Prof. Rena Latifa dan tim ini diperkenalkan sebagai inisiatif perintis untuk mendorong riset kelas dunia, mengkaji isu-isu kontemporer seperti kesehatan mental hingga filantropi dalam bingkai studi Islam yang modern.
Acara ini menghadirkan pakar lintas benua. Dari Amerika Serikat, hadir Prof. Kevin L. Ladd, Ph.D. (Indiana University South Bend) dan Prof. Daniel N. McIntosh, Ph.D. (University of Denver). Sementara dari dalam negeri, hadir Prof. Dr. Rena Latifa, M.Psi., Psi. (UIN Jakarta) dan Daniel Rabitha, M.Psi. (Peneliti BRIN), dan dimoderatori oleh Asep Haerul Gani.
Salah satu sorotan utama dalam acara ini adalah diseminasi hasil riset strategis bertajuk "Cyber Faith among Muslim Millennials". Temuan riset ini bahkan telah dikonversi menjadi sebuah buku panduan praktis berjudul "Beragama di Dunia Maya". Buku ini diharapkan menjadi kompas navigasi bagi generasi muda agar tidak tersesat di tengah riuh rendahnya informasi keagamaan digital.

Religiositas Muslim Indonesia di Dunia Maya
Prof. Rena Latifa dan Daniel Rabitha dalam pemaparannya mengungkap fakta menarik bahwa ruang digital kini telah berubah menjadi "alun-alun baru" bagi lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia. Bagi Gen-Z, gawai bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan sarana utama mengekspresikan iman, mulai dari pengajian virtual via Zoom, donasi zakat digital, hingga berguru pada "ustadz-influencer".
Fenomena ini menciptakan lanskap keagamaan yang sangat cair. Otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga tradisional atau kiai sepuh semata, melainkan bergeser ke tokoh-tokoh yang populer di YouTube dan TikTok. Namun, di balik kemudahan akses ini, tersimpan risiko pendangkalan pemahaman agama atau fenomena yang disebut sebagai "TikTok-isasi" iman.
Meski demikian, studi terhadap 1.034 responden Gen-Z ini membawa kabar yang melegakan: generasi ini tidak sepenuhnya meninggalkan cara lama. Mereka menerapkan gaya beragama "hibrida". Gen-Z menikmati fleksibilitas konten daring, namun tetap mengakui bahwa pertemuan tatap muka (offline) tak tergantikan untuk mendapatkan kedalaman ilmu dan ikatan emosional spiritual yang kuat.
Temuan riset juga menepis anggapan bahwa Gen-Z adalah konsumen pasif yang mudah disetir hoaks. Mayoritas responden menunjukkan sikap skeptis yang sehat; mereka aktif melakukan tabayyun atau memverifikasi kebenaran informasi. Mereka selektif memilih ustadz berdasarkan kredibilitas keilmuan, bukan sekadar viralitas semata, menjadikan internet sebagai alat pencari ketenangan batin yang tetap kritis.

Devosi Digital
Perspektif global diperkaya oleh paparan Prof. Kevin L. Ladd mengenai "Digital Devotion". Kevin mengajak audiens menyelami konsep "Pixelated Piety" atau kesalehan yang terpikselasi, di mana batas antara dunia nyata dan maya semakin kabur. Ia mempertanyakan esensi ibadah modern: apakah umat benar-benar "pergi" beribadah, atau sekadar "menonton" prosesi ibadah melalui layar kaca?
Kevin memberikan contoh nyata inovasi teknologi spiritual yang mencengangkan, seperti fenomena "AI Jesus" di Lucerne, "GitaGPT", hingga sajadah elektronik. Kehadiran teknologi ini memicu ketegangan antara pengalaman spiritual yang bersifat abadi (durable) dengan sensasi digital yang bersifat sementara (ephemeral), mengubah cara manusia mendefinisikan kesalehan.
Lebih jauh, Kevin menekankan dampak psikologis dari devosi digital ini. Ia melontarkan pertanyaan kritis: apakah teknologi ini berhasil membangun komunitas yang solid, atau justru memperdalam isolasi sosial? Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan teknologi berfungsi sebagai jembatan rekoneksi antarmanusia, bukan pemicu keterasingan di tengah keramaian maya.

Negosiasi Identitas Keagamaan Daring
Sementara itu, Prof. Daniel N. McIntosh menyoroti sisi lain dari interaksi digital, yakni negosiasi identitas. Dalam presentasinya, McIntosh menjelaskan bagaimana disintegrasi komunitas keagamaan fisik sering kali memicu tekanan psikologis, mendorong individu untuk mencari "suaka" di dunia maya guna merajut kembali jati diri mereka.
Menggunakan kerangka Networked Social Identity, McIntosh memaparkan bahwa media sosial kini berfungsi sebagai "ruang aman" yang menawarkan anonimitas. Ketika seseorang kehilangan identitas utama akibat meninggalkan kelompok lamanya, algoritma internet membantu mereka menemukan kelompok baru untuk berbagi cerita tanpa takut dihakimi.
Namun, fenomena ini bak pedang bermata dua bagi kesehatan mental. Di satu sisi, komunitas daring seperti grup Reddit atau Facebook bisa menjadi sarana penyembuhan trauma dan jembatan menuju "diri yang baru". Namun di sisi lain, terdapat risiko terjebak dalam disonansi kognitif yang berkelanjutan tanpa penyelesaian nyata.
McIntosh juga memperingatkan tentang munculnya "identitas baru" di ruang digital yang bisa menghambat perkembangan pribadi. Seringkali, individu hanya mendapatkan validasi emosional semata tanpa adanya kemajuan proses pendewasaan identitas pasca-dekonstruksi iman, membuat mereka terjebak dalam stagnasi psikologis.

Pada akhirnya, Studium Generale ini menyimpulkan bahwa Cyberfaith adalah realitas tak terelakkan yang harus dihadapi dengan bijak. Internet hanyalah alat; kuncinya terletak pada bagaimana pengguna menyeimbangkan kemudahan teknologi dengan kedalaman spiritualitas.
Acara ditutup dengan optimisme bahwa melalui peluncuran Indonesian Lab of Anthropo-psychology of Religion and Spirituality, UIN Jakarta akan terus menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi akademik yang relevan. Dengan memahami fenomena Cyberfaith, masyarakat diharapkan mampu menjaga keaslian iman di tengah derasnya arus digitalisasi.(JA)